Indeks Kategori
KATA MEREKA

KATA MEREKA
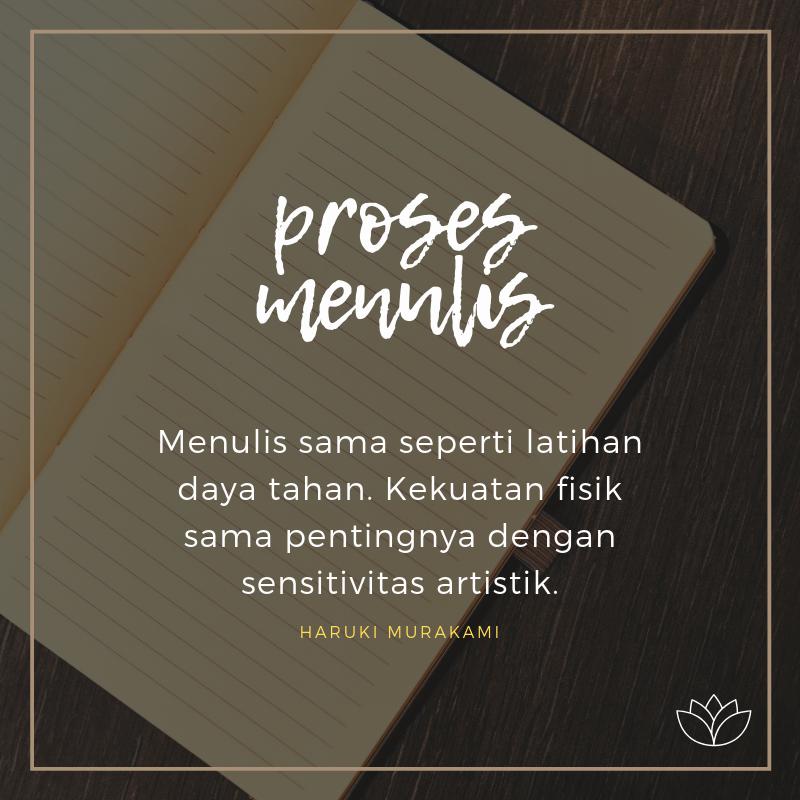
-
Bergabung dengan 6.740 pelanggan lain
Like us on FB
Jhumpa Lahiri
Ayahku, yang kini berusia 78 tahun, adalah orang yang metodis. Selama tiga puluh sembilan tahun, ia hanya punya satu pekerjaan: menyusun daftar buku-buku di perpustakaan kampus. Setiap pagi, ia minum dua gelas air putih, lantas berjalan kaki selama satu jam dan menghabiskan jumlah waktu yang sama untuk membersihkan giginya menggunakan benang sutera setiap malam sebelum tidur. Ketika menggambarkan sosok ayahku, “spontan” bukanlah kata yang cocok. Saat dia berkendara ke tempat-tempat baru, ia tidak pernah bisa menikmati rasanya tersesat.
Di dalam dapur pun kebiasaannya tetap sama. Ia punya peraturan sendiri, seperti menghitung butir kismis yang ia campur ke dalam bubur oatmeal (lima belas) dan ia tidak pernah memasak air lebih dari yang dibutuhkan saat hendak menyeduh teh. Ayahku sudah hafal luar kepala berapa takaran beras yang dibutuhkan untuk memberi makan empat, atau empat puluh, atau seratus empat puluh orang. Dia juga punya reputasi untuk meng-andaj — kata Bengali yang berarti “estimasi” — di mana dia secara akurat mengukur takaran bahan yang dibutuhkan untuk memasak. Kemampuannya itu tidak jarang membuat juru masak manapun yang ia temui ternganga. Ayahku adalah si peramal beras, kurasa itu istilah yang lebih tepat.
Namun ada nasi lain yang membuat ayahku lebih dikenal di kalangan keluarga dan kerabat kami. Bukan nasi putih, yang dimasak seperti pasta dan ditiris menggunakan saringan, yang biasa disantap orang Bengali di waktu makan malam. Nasi lain itu adalau pulao, nasi eksotis asal Persia yang dipersiapkan dengan cara dipanggang dan dilumuri mentega. Nasi pulao juga kerap disajikan di acara-acara besar. Aku sering melihat ayahku memasak jenis nasi tersebut. Caranya: beras basmati ditumis bersama mentega, batangan kayu manis, cengkeh, daun salam, serta butiran kapulaga. Lalu ia akan menambahkan kacang mete yang telah dibelah dua dan kismis (berbeda dengan kismis yang dicampurnya ke dalam bubur oatmeal, kismis untuk nasi pulao berwarna keemasan, bukan hitam). Jahe yang telah dihancurkan juga dicampur ke dalamnya, beserta garam dan gula, biji dan bunga pala, serat kumkum kalau ada, dan bila itu tak ada ia akan menggantinya dengan kunyit halus. Sejumlah air kemudian ditambahkan pada campuran tersebut, lalu ia akan menunggu sampai beras itu mulai mendekati titik tanak dan sebagian besar air telah menguap.
Langkah selanjutnya, ayahku akan meratakan nasi setengah matang itu ke atas nampan kue. (Ia lebih suka menggunakan nampan kue yang terbuat dari bahan alumunium dan biasa digunakan hanya sekali saja, sebelum akhirnya didaur ulang. Ia melakukan ini bahkan jauh sebelum hukum daur-ulang ditetapkan*). Kemudian dengan jemarinya, ia menyipratkan air di atas nasi, persis seperti para pastur gereja saat menyipratkan air suci ke umatnya. Setelah itu, ia membungkus nampan itu dengan kertas timah dan memasukkannya ke dalam oven. Ia baru mengeluarkan nasi itu setelah benar-benar tanak, dan butir-butirnya tidak saling menempel.
Anehnya, meski aku tahu bumbu yang diperlukan dan segala teknik memasak nasi pulao, aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Dan aku takkan berani mencoba. Resep itu hanya milik ayahku, dan tak pernah dicatat atau dibagikan kepada siapa-siapa. Setiap kali ia memasak nasi itu, hasilnya selalu sempurna; namun rasanya tidak pernah membosankan. Nasi pulao tersebut telah menjadi bagian dari identitas ayahku, sesuatu yang ia sempurnakan seorang diri, yang benar-benar miliknya secara intelektual. Sajian yang akan hilang jika nanti ia tak lagi ada bersama kami.
Pada tahun 1968, ketika usiaku baru tujuh bulan, ayahku membuat nasi pulao untuk pertama kalinya. Kami tinggal di London saat itu, di Finsbury Park, dan kedua orangtuaku harus berbagi dapur, yang letaknya di atas loteng dan hanya bisa dijangkau dengan menaiki tangga curam, dengan pasangan asal Bengali lainnya. Ayahku memasak nasi itu untuk merayakan annaprasan-ku, sebuah ritual yang dilakukan masyarakat Bengali saat anak-anak mereka mulai menyantap makanan padat. Acara itu juga biasa dikenal dengan nama bhath, yang dalam bahasa Bengali berarti “nasi tanak”. Di dalam oven yang tergabung dengan kompor, yang lebarnya tidak lebih dari 50 cm, ayahku memanggang nasi pulao untuk menjamu tiga puluh lima tamu undangan.
Sejak itu, ia rajin memasak nasi pulao untuk jamuan acara annaprasan anak-anak teman-temannya, juga untuk pesta ulang tahun dan peringatan pernikahan, serta baby shower, resepsi pernikahan, dan pesta perayaan bagi kakak perempuanku yang waktu itu baru saja menerima gelar doktor. Selama beberapa dekade, setelah kami pindah ke Amerika Serikat, para tamu yang menikmati nasi pulao ayahku bisa mencapai empat ratus orang. Ia kerap diminta menyajikan nasi andalannya itu di sejumlah acara yang diorganisir oleh Prabasi, institusi budaya bagi para warga Bengali yang tinggal di negara bagian New England. Dari situ ayahku sering sekali diundang ke tempat-tempat resmi — sekolah, gereja, pusat kebudayaan — di mana ia bisa memasak nasi pulao menggunakan oven dan kompor besar. Hal ini tak pernah membuatnya grogi. Kurasa bila ada yang minta, ia sanggup memasak nasi pulao hanya dengan menggunakan perangkat gerobak hot dog jalanan.
Ada kalanya ia kekurangan rempah-rempah yang dibutuhkan, dan ia terpaksa mengganti kacang mete dengan kacang almond, atau ketika kismis yang tersedia di lemari dapur sahabatnya bukan kismis berwarna keemasan seperti yang biasa ia gunakan. Meski begitu, ia tetap memasak nasi pulao. Bumbu yang ia gunakan boleh standar, namun tangannya selalu bekerja dengan optimis.
Ketika putra dan putriku masih bayi, aku dan suamiku mengadakan perayaan annaprasan untuk mereka. Untuk itu, kami menyewa jasa katering. Namun ayahku tetap membuat nasi pulao andalannya, dan menyiapkannya di rumahnya sendiri di Rhode Island. Ia kemudian menyimpannya di bagasi mobil sampai tiba di Brooklyn. Acara itu, kedua-duanya, diadakan di Park Slope, di gedung lembaga Society for Ethical Culture**. Pada tahun 2002, ketika putraku mencicipi nasi untuk pertama kalinya, ayahku menghangatkan nampan-nampan berisi nasi pulao setengah matang di lokasi perayaan. Di ruang bawah tanah gedung itu ada oven raksasa yang bisa ia pergunakan. Namun pada tahun 2005, ketika tiba giliran putriku untuk mencicipi nasi untuk pertama kalinya, pihak perwakilan lembaga tidak mengijinkan ayahku menggunakan oven itu dengan alasan ayahku bukan juru masak profesional. Maka ayahku memindahkan nasi pulao andalannya dari atas nampan alumunium ke dalam piring panggangan yang terbuat dari kaca dan menghangatkannya di microwave — porsi demi porsi yang telah ia siapkan untuk menjamu seratus orang tamu. Saat aku tanya kepada ayahku tentang pengalamannya waktu itu, ia sama sekali tidak terlihat kesal. “Tak masalah,” katanya. “Microwave itu cukup besar, kok.” FL
Januari 2016 © Hak cipta Fiksi Lotus dan Jhumpa Lahiri. Tidak untuk dijual, digandakan, ataupun ditukar.
#KETERANGAN:
(*) Pada tahun 1989, pemerintah daerah negara bagian New York menetapkan hukum daur-ulang yang mengharuskan setiap warganya untuk memisahkan sampah domestik dalam kategori daur-ulang (kertas, pecah-belah, plastik, dll.) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar Departemen Sanitasi dapat mengolah sampah dengan lebih baik dan terukur.
(**) Brooklyn Society for Ethical Culture adalah sebuah lembaga sosial yang didirikan pada tahun 1907 dan beralamat di Brooklyn. Lembaga ini membuka pintunya bagi siapa saja yang ingin mengadakan acara sosial atau program belajar bagi orang dewasa dan anak-anak, selama untuk tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat.
#CATATAN:
> Esai ini bertajuk Rice karya JHUMPA LAHIRI dan pertama kali diterbitkan di The New Yorker pada tahun 2009.
>> JHUMPA LAHIRI adalah seorang penulis India-Amerika yang telah memenangkan berbagai penghargaan, termasuk Pulitzer Prize for Fiction untuk karyanya yang berjudul Interpreter of Maladies (1999). Karya-karya lainnya yang telah mendunia adalah Unaccustomed Earth, The Namesake dan Lowland. Ia termasuk salah satu penulis berdarah India yang paling aktif mengangkat isu-isu kehidupan imigran di luar India.
Saya mengenal namanya di buku2 ttg teori sastra, tp baru kali ini membaca karyanya
SukaDisukai oleh 1 orang
saya menikmati membaca terjemahan mbak maggie, terimakasih
SukaDisukai oleh 1 orang
Menarik sekali membaca karya sastrawan yang sudah mendunia.
SukaDisukai oleh 1 orang
tulisannya sangat bersahaja.. terimakasih kak Maggie sudah menerjemahkan esai ini.. salam jaya selalu.
SukaDisukai oleh 1 orang
Tulisan ini sungguh … bagaimana ya menjelaskannya? Entahlah, tapi saya suka. ^^ Makasih kak Maggie
SukaSuka
maksud dari cerita ini apa ya? aku cma bsa nangkep yg bagian ‘microwave itu cukup besar’ 😦
SukaSuka
Seperti membicarakan nasi, tetapi bukan. Ini lebih bercerita mengenai sosok Ayah yang begitu peduli, hangat dan sangat baik.
SukaSuka